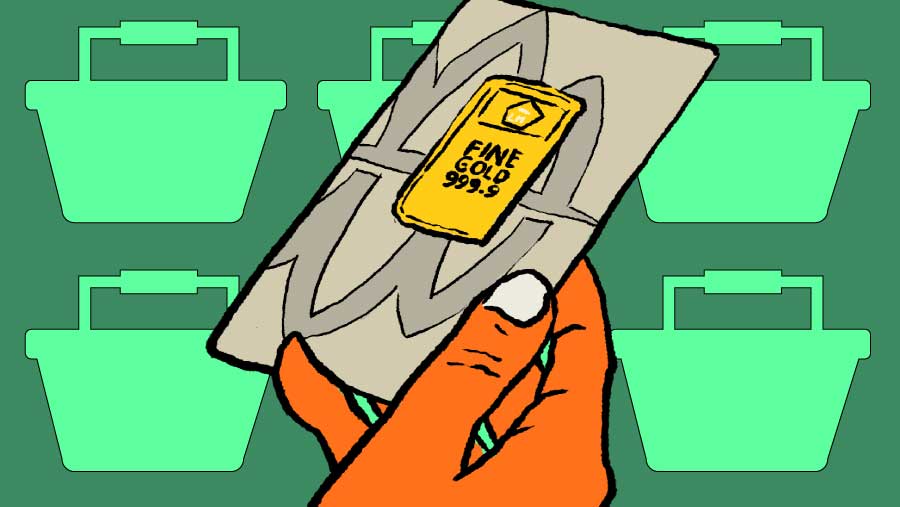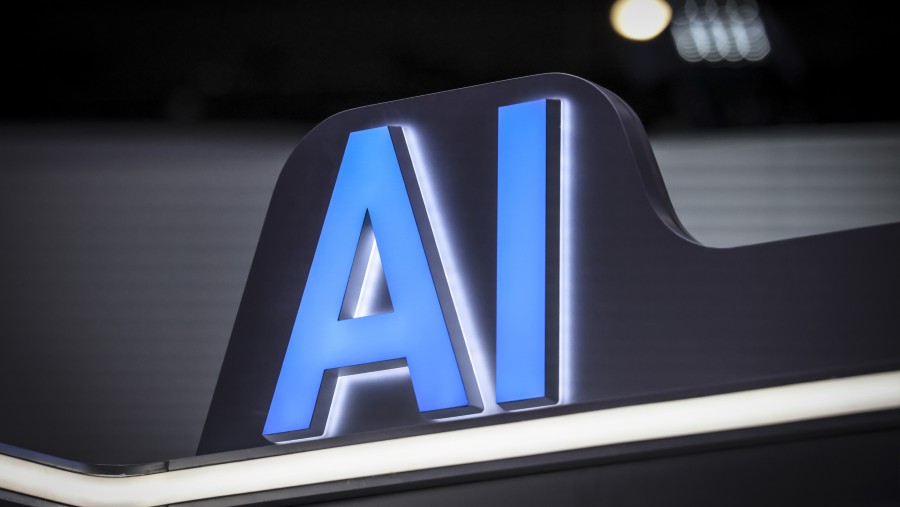Bhima menambahkan bahwa harga nikel terlalu rendah, industri tengah yang tidak dibangun atau hollow in the middle, dan dampak lingkungan yang terlanjur berisiko tinggi menjadikan negara produsen kehilangan daya tawar di hadapan pembeli baik industri stainless steel dan kendaraan listrik.
“Penguatan kerja sama antar negara produsen mineral kritis harus memasukkan prinsip tata kelola, industrialisasi yang berkelanjutan dan pro terhadap standar lingkungan yang lebih ketat, termasuk tidak menambah jumlah PLTU batubara di kawasan industri.” tutur Bhima.
Dalam kesempatan yang sama, Jezri Krinsky dari Institute for Economic Justice, Afrika Selatan menambahkan perlu adanya aliansi untuk mengangkat isu-isu yang diakibatkan oleh ekstraksi mineral kritis, termasuk kondisi pekerja yang buruk, bahaya kesehatan bagi masyarakat lokal, degradasi lingkungan, dan distribusi kekayaan yang tidak adil.
“Aliansi ini harus melibatkan berbagai kelompok terdampak, seperti petani, masyarakat adat, pekerja, dan komunitas perkotaan yang selama ini menanggung dampak terbesar dari eksploitasi mineral kritis,” ujar Jezri.
Terlepas dari ekspansi industri ekstraksi mineral, Jezri menyebut biaya lingkungan dan sosial yang ditanggung negara penghasil jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonominya. Banyak deposit mineral terkaya terletak di wilayah yang sensitif secara ekologis dan merupakan tanah adat, di mana aktivitas pertambangan telah menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan peminggiran masyarakat lokal.
Theiva Lingam dari Friends of the Earth (FoE) Malaysia menyebut penambangan di daerah yang sensitif terhadap lingkungan tidak boleh diizinkan.
“Potensi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki membutuhkan kerangka regulasi yang kuat dan komitmen terhadap praktik berkelanjutan yang benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ucap Theiva.
Para peserta konferensi juga menyoroti urgensi peningkatan akuntabilitas perusahaan dan transparansi data dalam rantai pasokan mineral kritis. Mereka menuntut pengungkapan wajib terkait sumber bahan baku (traceability), pendanaan, serta dampak lingkungan dari operasi pertambangan.
Pasalnya, saat ini hanya segelintir perusahaan yang secara terbuka mengungkapkan asal-usul nikel mereka, sehingga menyulitkan pengawasan dan regulasi yang efektif.
Dengan adanya seruan tersebut, konferensi menegaskan perlunya pendekatan yang lebih berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya mineral kritis, memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak lagi hanya menguntungkan segelintir aktor, tetapi juga melindungi hak masyarakat dan kelestarian lingkungan di negara-negara penghasil mineral kritis.
GNI terancam tutup
Kejatuhan raksasa baja nirkarat China, Jiangsu Delong Nickel Industry Co, membawa kabar tidak sedap terhadap salah satu smelter nikel di Indonesia yang terafiliasi dengan korporasi tersebut, yaitu PT GNI.
Smelter Gunbuster di Morowali dikabarkan telah memangkas produksinya dan hampir tutup total hanya beberapa bulan setelah perusahaan induknya di China, Jiangsu Delong, kolaps.
Menurut para narasumber yang mengetahui situasi tersebut kepada Bloomberg, GNI menunda pembayaran kepada pemasok energi lokal dan tidak dapat memperoleh bijih nikel.
Smelter GNI tersebut kemungkinan akan segera menghentikan produksi jika situasi terus berlanjut, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masalah tersebut sensitif.
Gunbuster tidak membalas permintaan tanggapan dari Bloomberg.
Saat ini, pasokan bijih bagi industri smelter di Indonesia dikabarkan telah ketat selama hampir setahun akibat kurangnya kuota penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Hal itu memperburuk kesulitan Gunbuster, yang sudah menderita akibat keruntuhan induknya Delong. Bisnisnya telah menderita akibat perlambatan ekonomi China dan persaingan ketat dari Tsingshan Holding Group, yang juga memiliki operasi besar di Indonesia.
(wep)