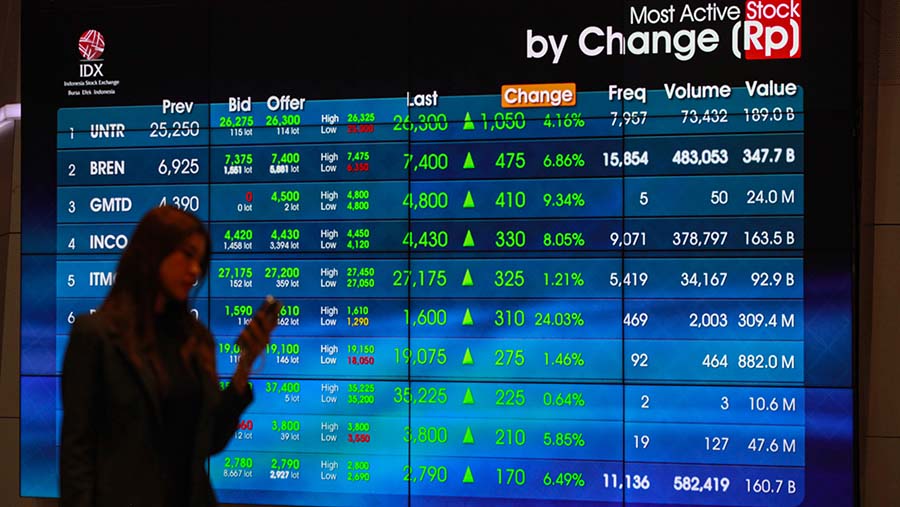Lonjakan ULN dari Tiongkok terutama disumbang oleh sektor swasta di mana proporsinya mencapai 94,3% dari total ULN Tiongkok yang tercatat, atau senilai US$21,4 miliar. Nilai pinjaman China itu mencapai 11% dari total ULN swasta, dan menjadi yang terbesar ketiga setelah pinjaman dari Singapura dan AS per Juli lalu.
Sektor swasta campuran (joint venture) menyumbang proporsi terbesar ULN sektor swasta senilai US$52,44 miliar. Sedang melihat sektor ekonomi, ULN swasta di sektor industri manufaktur masih mendominasi dengan nilai US$47,5 miliar, disusul sektor pertambangan dan penggalian US$32 miliar. Dua sektor itu membukukan kenaikan posisi ULN dalam 10 tahun terakhir, masing-masing sebesar 64% dan 18%.
Nilai ULN swasta yang jatuh tempo kurang dari setahun ke depan juga tidak kecil. Nilainya mencapai US$48,61 miliar, di mana sebanyak 53,5% disumbang oleh ULN jangka pendek korporasi nonkeuangan.
Dari keseluruhan ULN, nilai yang jatuh tempo setahun ke depan mencapai US$74,55 miliar, terutama disumbang oleh sektor swasta.
Bila melihat posisi kesehatan utang, rasionya semakin meningkat pada kuartal II-2024. Rasio utang jangka pendek berdasarkan jangka waktu asal terhadap total utang, misalnya, naik jadi 14,33%, tertinggi sejak 2015. Sedangkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto naik jadi 29,87%, tertinggi sejak kuartal 1-2023.
Kredit Bank Lokal Masih Kecil
Bahlil dalam forum investor pekan ini menyatakan, 85% industri penghiliran nikel masih dikuasai oleh asing. Hal itu, menurutnya karena partisipasi perbankan dalam negeri yang masih minim dalam mendanai proyek hilirisasi nikel di dalam negeri.
Ketika perbankan luar negeri yang memberikan kredit pada industri nikel, biasanya ada persyaratan yang diberikan termasuk di dalamnya adalah transaksi harus dilakukan di rekening bank pemberi pinjaman. Hasil transaksi akan dipotong oleh utang pokok dan bunga pinjaman yang biasanya mencapai 60% dari keuntungan sehingga dana hasil hilirisasi nikel itu kembali ke bank asing juga yang mendanai proyek.
Aliran cuan yang lebih banyak dinikmati oleh asing bisa dialihkan ke dalam negeri, kata Bahlil, bila saja perbankan dalam negeri atau investor lokal makin banyak yang terjun dan membiayai proyek penghiliran.
Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan, sampai Agustus lalu, laju penyaluran kredit ke industri pengolahan terkait hilirisasi masih tumbuh kencang, hingga 10,58% year-on-year, dibanding sebelumnya yang hanya tumbuh 5,27%. Namun, bila dibandingkan total penyaluran kredit bank keseluruhan, pengucuran pinjaman ke sektor tersebut memang masih kecil, hanya 2,61% dari total kredit pada Agustus.
Jebakan Utang China
Pernyataan Bahlil itu seolah menggemakan lagi kritik yang pernah dilontarkan oleh almarhum Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri tahun lalu. Faisal kala itu menilai, jorjoran program penghiliran yang dihelat Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir, sejatinya lebih menguntungkan China alih-alih industri di dalam negeri.
"Kalau hilirisasi, sekadar dari bijih nikel menjadi NPI atau feronikel, tetapi 90% diekspor ke China. Jadi penghililran di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China,” kata Faisal ketika itu.

Studi lain yang pernah dilansir oleh Centre of Law and Economic Studies (CELIOS) pada 2023, menyoroti risiko 'jebakan utang China' menyusul keterlibatan Tiongkok yang semakin dominan dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, baik itu proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (WHOOSH) hingga proyek hilirisasi.
Dominasi China dimulai sejak Indonesia terlibat dalam Belt and Road Initiative yang digadang oleh Tiongkok sejak 2013 melalui sejumlah proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar dolar AS.
Indonesia termasuk di jajaran teratas negara yang terlibat inisiatif yang disebut-sebut sebagai Jalur Sutera Baru China itu. Jumlah proyek yang digarap cukup banyak -mencapai 71 proyek pada 2021 menurut catatan AidData, hanya kalah oleh Kamboja yang tercatat memiliki 82 proyek terkait Inisiatif Sabuk dan Jalan China.
China berhasil membenamkan investasi kurang lebih US$ 1 triliun di Asia Tenggara khususnya di empat negara sampai 2019 lalu, yaitu Indonesia, Vietnam, Kamboja dan Singapura. Beberapa sektor yang banyak digarap adalah transportasi, tambang, pembangkit listrik dan air, dan lain sebagainya.
Semakin dominannya China dalam pembangunan berbagai infrastruktur strategis RI, memicu kecemasan karena dalam perjalanannya ternyata muncul banyak permasalahan yang mengkhawatirkan. Seperti pembengkakan biaya proyek, bunga pinjaman yang sangat mahal, persyaratan tenaga kerja bahkan untuk jenis pekerjaan kasar/non-ahli, hingga isu keselamatan kerja.
"Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar berkaca dari negara-negara yang terlibat dalam proyek Belt and Road Initiative yang beberapa telah dinyatakan gagal bayar. Ada banyak faktor lain juga yang bisa menyebabkan risiko jeratan utang di antaranya karena China memberi pembebanan skema kredit yang tinggi," kata M. Zulfikar Rakhmat dan Yeta Purnama, analis CELIOS, dalam kajian tersebut.
Bukan cuma bunga tinggi, syarat pinjaman yang mewajibkan negara pengutang membeli 70% bahan baku dari China dan mempekerjakan tenaga kerja dari Tiongkok dalam jumlah besar, termasuk tenaga kerja kasar, juga memicu polemik tersendiri. Belum lagi kewajiban bagi negara pengutang memakai mata uang lokal, rupiah dan yuan, dalam transaksi juga melahirkan risiko mengingat langkah China yang sering mendevaluasi mata uangnya.
"Pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan RI dalam Inisiatif tersebut bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Pemerintah perlu menyadari bahwa dalam proses implementasi Belt and Road, China lebih membutuhkan Indonesia daripada sebaliknya karena posisi penting RI yang strategis di Asia Tenggara," demikian disebut dalam hasil kajian tersebut.
AidData mencatat, ada sekitar 9 proyek infrastruktur di bawah payung Belt and Road Initiative di Indonesia yang terindikasi skandal dan kontroversi, mulai dari permasalahan biaya utang, isu lingkungan hidup, juga tata kelola yang buruk, kecelakaan kerja dan persoalan ketenagakerjaan.

Sejumlah negara sejauh ini banyak yang telah terjatuh dalam jebakan utang China. Misalnya, Uganda yang mendapatkan pinjaman senilai US$ 207 juta dari Tiongkok untuk pembangunan bandara internasional. Namun, karena tidak mampu membayar utang, negeri di Afrika itu harus merelakan kepemilikan bandara pada kreditur.
Sri Lanka juga bernasib mirip. Negeri di Asia Selatan itu menerima pinjaman sekitar US$ 1,5 miliar dari China untuk membangun pelabuhan. Akibat tidak mampu membayar, hak milik pelabuhan itu jatuh ke Tiongkok.
Hal yang sama terjadi pada Zimbabwe yang mengalami krisis utang akibat 'kecanduan' utang dari China dan berakhir mengizinkan yuan alias renminbi, mata uang Tiongkok, sebagai mata uang alternatif yang legal sejak 2016.
"Banyak negara yang menerima investasi China mengalami masalah, salah satunya karena mereka tidak memiliki keahlian keahlian teknis untuk menilai ketentuan kontrak proyek atau kesinambungan mekanisme utang serta kesulitan menavigasi proses sengketa dalam skema Belt and Road Initiative. Pasalnya, pinjaman itu beroperasi di luar sistem moneter standar internasional sehingga perlindungannya juga terbatas. Sebagai konsekuensi, negara yang terjebak punya lebih sedikit pilihan mencari bantuan ketika terlilit utang sehingga menempatkan China dalam posisi diuntungkan karena mendapat konsesi dan aturan pinjaman yang ditetapkan sendiri," tulis Zulfikar dan Yeta.
Indonesia sebaiknya waspada dan menyiapkan mitigasi akan potensi masalah-masalah yang timbul dari hal tersebut, sebelum terlambat.
-- dengan bantuan Dovana Hasiana dan Azura Yumna.
(rui/aji)