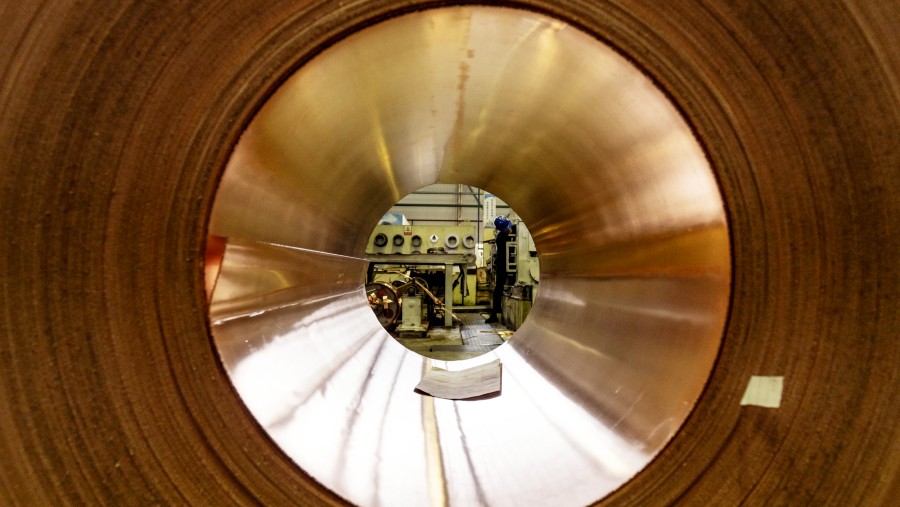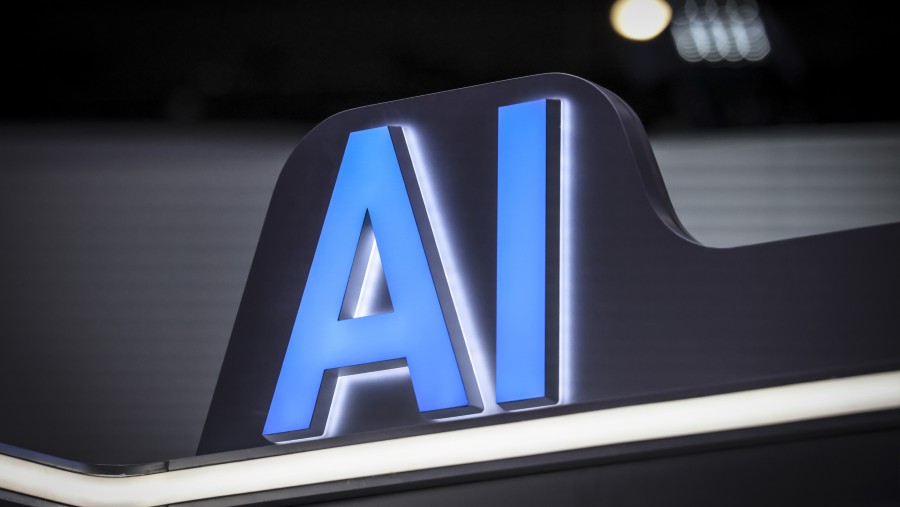Lalu, sebenarnya apa itu 'nikel hijau'?
Dilansir melalui situs Easy Skill, ‘nikel hijau’ atau kadang juga disebut sebagai nikel berkelanjutan (sustainable nickel), diproduksi dengan menerapkan praktik penambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara atau minyak, pengurangan dan pengolahan limbah khususnya dalam proses hidrometalurgi dan remediasi air.
Adapun, tambang ‘nikel hijau’ berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal dalam isu-isu sosial. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kesempatan kerja, pelatihan, dan pengembangan keterampilan.
Sayangnya, nikel jenis ini masih sulit mendapatkan harga premium di pasar lantaran ongkos produksinya tidak efisien jika dibandingkan dengan nikel-nikel yang diproduksi di Indonesia.

Bagaimana dengan nikel yang diproduksi RI?
Sebuah riset dari Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), bertajuk Debunking the Value-added Myth in Nickel Downstream Industry, melaporkan bahwa industri nikel di Indonesia pengolahannya berbasis pembangkit batu bara.
Dengan demikian, sebaran emisi dari industri logam di Indonesia berubah drastis sejak hilirisasi nikel dimulai, ditandai dengan pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020. Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku menjadi titik utama sumber emisi imbas masifnya perkembangan industri nikel yang pengolahannya berbasis batu bara.
“Hampir 80% dari total emisi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara berasal dari proses pengolahan nikel. Sisanya berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik ke unit-unit smelter nikel,” sebagaimana dikutip melalui laporan tersebut.
Pertumbuhan industri dari nikel yang pesat, jika tidak diatur, akan menyebabkan lebih dari 3.800 kematian pada tahun 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.
Bukan hanya dari sisi polusi dan kesehatan, emisi dari smelter dan PLTU captive di tiga provinsi yang diteliti diperkirakan akan memberikan dampak beban ekonomi tahunan sebesar US$2,63 miliar atau Rp40,7 triliun pada 2025.
“Tanpa intervensi yang berarti untuk memitigasi emisi, beban ini diperkirakan akan meningkat lebih dari 30% atau US$3,42 miliar (Rp53 triliun) pada 2030,” sebagaimana dikutip melalui laporan tersebut.

Sebelumnya, orang terkaya di Australia, Andrew Forrest, mendesak LME untuk membedakan klasifikasi antara nikel "kotor" dan "bersih" dalam perdagangan logamnya. Pernyataan tersebut dibuat setelah bisnis logam pribadinya mengumumkan penutupan tambang baru-baru ini.
Forrest mengatakan kepada wartawan di Canberra pada Senin (26/2/2024) bahwa LME harus mengklasifikasikan nikel berdasarkan emisi karbon. Dengan demikian, pelanggan dapat membuat pilihan mengenai produk yang mereka transaksikan.
Dia menambahkan, beberapa perusahaan menggunakan baterai dari nikel murah yang ditambang di Indonesia, yang dikenal dengan jejak emisi tinggi dan standar lingkungan yang dipertanyakan.
"Anda ingin punya pilihan untuk membeli nikel bersih jika Anda bisa," kata Forrest. "Jadi, LME harus membedakan mana yang kotor dan yang bersih. Keduanya adalah produk yang berbeda, dan memiliki dampak yang sangat berbeda."
(dov/wdh)