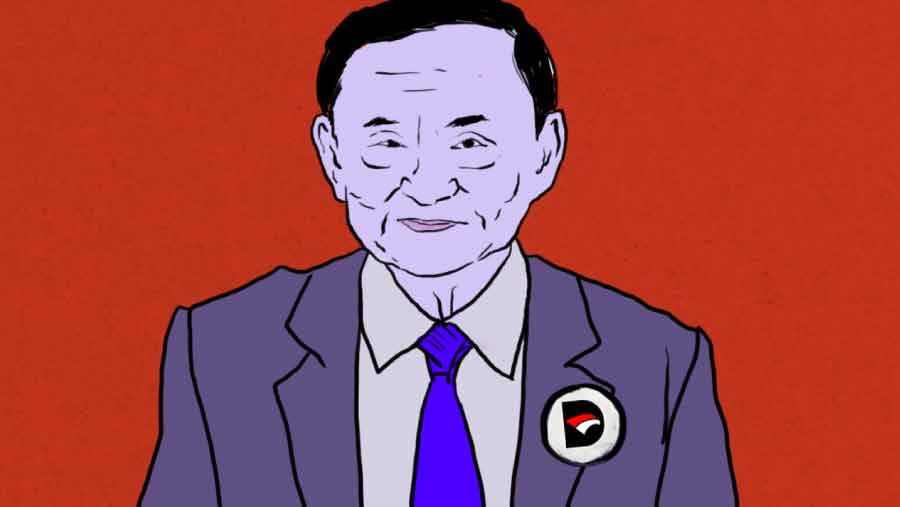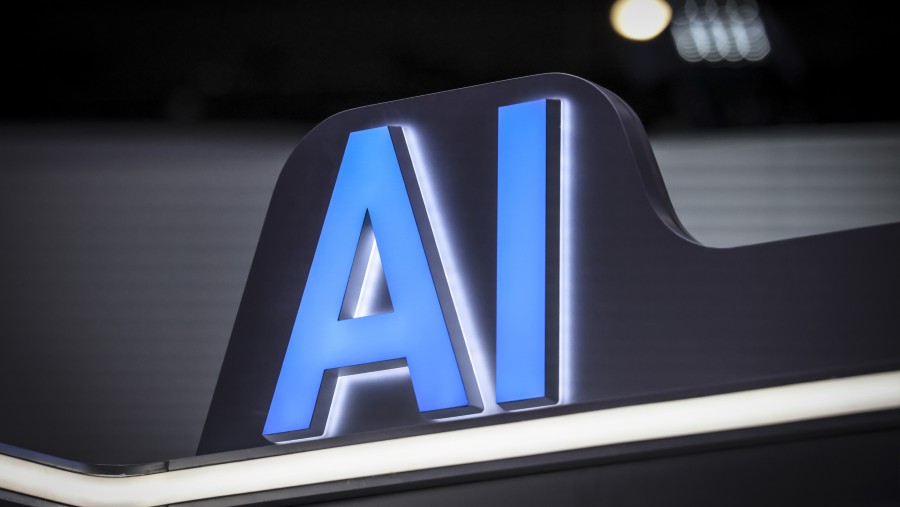Bloomberg Technoz, Jakarta – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan setidaknya terdapat 3 permasalahan yang ada dalam pengembangan Food Estate, meski diklaim sudah berhasil oleh pemerintah.
Pertama, Food Estate melanggar kaidah akademik yang terdiri dari 4 pilar. Di antaranya adalah kelayakan tanah dan agroklimat, ketersediaan infrastruktur berupa saluran irigasi dan jalan usaha tani, aspek budi daya dan teknologi, serta sosial dan ekonomi.
“Satu saja dari keempat pilar tersebut tidak dipenuhi, pasti kacau. Itu yang terjadi di semua Food Estate,” ujar Dwi saat dihubungi, Kamis (25/1/2024).
Hal itu yang menyebkan terdapat setidaknya 6 proyek Food Estate yang gagal. Di antaranya adalah proyek lahan gambut 1 juta hektare, proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada era Susilo Bambang Yudhoyono seluas 1,23 juta hektare, Food Estate Ketapang 100.000 hektare, Food Estate Bulungan 300.000 hektare, proyek Rice Estate 1,2 juta hektare, dan Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Kedua, proyek saat ini tidak sesuai dengan definisi asli dari Food Estate. Dwi menyebutkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian cenderung selalu menggunakan istilah Food Estate pada program yang sebenarnya hanya merupakan intensifikasi dan optimasi lahan.

Tak Sesuai Khitah
Merujuk pada definisi dari Food Estate, kata Dwi, harus terdapat pengelolaan lahan besar oleh perorangan, keluarga atau perusahaan serta investor pangan.
Suatu proyek tidak layak disebut sebagai Food Estate bila tidak ada investor pangan yang menanamkan modal untuk memproduksi pangan di wilayah yang disediakan pemerintah.
“Food Estate di Pulau Pisau yang dinyatakan berhasil itu bukan Food Estate, itu program intensifikasi lahan. Proyek di Sumatra Utara untuk hortikultura itu optimalisasi lahan, bukan Food Estate. Jadi sudah ada petani, lahannya terbengkalai kemudian diolah itu namanya optimalisasi lahan,” ujarnya.
Menurut Dwi, program Food Estate yang sesuai dengan definisi adalah proyek MIFEE di mana terdapat investor yang menggelontorkan dana.
Ketiga, terdapat pergantian program pengembangan pangan setiap pergantian presiden.
“Setiap presiden ganti wilayah. Jadi uang puluhan triliun dihamburkan tidak jelas, kan itu yang terjadi selama ini. Setiap ganti presiden ganti lokasi. Lalu bagaimana uang dihamburkan puluhan triliun hanya untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya sama sekali, untuk sesuatu yang gagal total. Kasian rakyat wong itu uang rakyat,” ujarnya.

Solusi Ketahanan Pangan
Seiring dengan itu, Dwi juga menjelaskan solusi untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia. Pertama, menetapkan wilayah pasti yang bakal dikembangkan untuk produksi pangan.
Dalam hal ini, pemerintah bisa menetapkan wilayah tertentu di lahan bekas gambut seluas 1 juta hektare yang memenuhi 4 pilar yang sebelumnya disebutkan. Dengan demikian, pemerintah bisa berinvestasi untuk produksi pangan dan sekaligus perbaikan lingkungan karena menggunakan lahan bekas gambut.
“Dan tidak usah mimpi besar-besar, menyebut sebagai mega proyek. Hanya butuh beberapa ribu hektare di wilayah tertentu kita tetapkan itu sebagai wilayah pengembangan. Lalu, lupakan istilah Food Estate,” ujarnya.
Sementara itu, untuk program yang disebutkan pemerintah sebagai Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara bisa tetap dilanjutkan selama ada petani yang menggarap lahan tersebut.
Namun, terdapat risiko bahwa lahan tersebut bakal ditinggalkan oleh petani bila tidak memberikan nilai manfaat secara ekonomi karena tidak memenuhi 4 pilar kaidah akademik.
Kedua, kembali menggerakkan program transmigran mengolah lahan untuk produksi pangan atau pengelolaan perkebunan. Sehingga para transmigran yang memasuki wilayah baru mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk menggarap lahan yang tersedia untuk produksi pangan dan perkebunan.
“Lebih baik jangan sertifikat hak milik. Sebab banyak transmigran lama dari wilayah lain mendaftar dan lahan dijual. Sehingga lebih baik jangan ada sertifikat kepemilikan di sana kalau mereka tidak sanggup mengelola diserahkan pada pemerintah bukan kemudian diperjualbelikan,” ujarnya.
(dov/wdh)