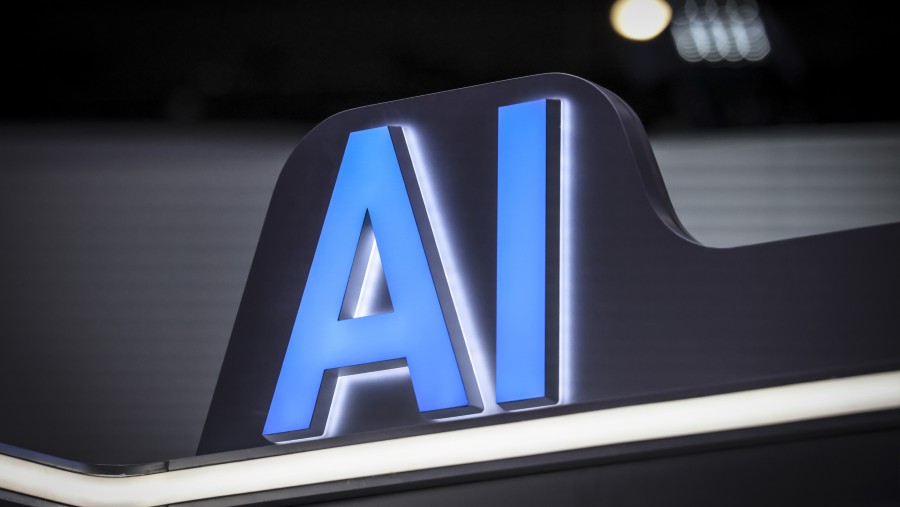Bloomberg Technoz, Jakarta - Sebanyak 69 dari 100 penduduk Indonesia adalah orang dengan pendapatan menengah bawah, menurut publikasi yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (20/12/2023). Jumlah yang besar nyatanya tidak membuat kelompok masyarakat ini mendapatkan perhatian yang semestinya supaya bisa membantu peningkatan kesejahteraan.
Sebaliknya, hasil analisis yang dilakukan oleh BPS, menyebut, kelompok berpendapatan menengah bawah di Indonesia sejauh ini masih kesulitan menikmati akses pendidikan dan teknologi, juga kesehatan, perlindungan sosial maupun jaminan pekerjaan. Dalam lanskap itu, kualitas hidup masyarakat kelas menengah di Indonesia sejatinya masih rendah kendati dari sisi pendapatan sudah terlepas dari jerat kemiskinan.
Perlu terobosan kebijakan yang memberi bobot lebih besar pada peningkatan kualitas hidup juga keadilan dalam sistem ekonomi serta politik. Isu yang semestinya menjadi perhatian utama para calon presiden yang berlaga dalam Pemilu dan Pilpres 2024, alih-alih hanya berfokus pada pembenahan ketimpangan dalam arti sempit.
Kelas menengah bawah di Indonesia memang menempati posisi yang dilematis. Di satu sisi, pendapatan mereka tidak bisa dimasukkan dalam kategori miskin sehingga tidak tersentuh akses perlindungan sosial seperti bantuan sosial yang banyak digalakkan pemerintah.
Namun, kelompok ini rentan terjatuh dalam kemiskinan bila sewaktu-waktu terjadi guncangan dalam perekonomian seperti yang terlihat kala pandemi Covid-19 melantakkan ekonomi.
Gelombang pemutusan hubungan kerja yang masif dan sempitnya lapangan kerja akhirnya melemparkan banyak penghuni kelompok ini ke situasi lebih buruk. Padahal, sebelum turun kelas pun kelompok ini sudah menghadapi banyak kesulitan.
Terkait pendidikan dan akses teknologi misalnya, baru 4,67% dari kelompok ini yang memanfaatkan teknologi seperti komputer, laptop atau tablet. Sementara yang berhasil menamatkan pendidikan hingga SMA baru sebesar 30,14%.
Akses pada pendidikan dan teknologi yang masih rendah alhasil mempengaruhi pula daya tawar kelas menengah bawah terhadap pekerjaan yang layak.
"Data SUSENAS mencatat, 68% kepala rumah tangga pada kelompok menengah bawah adalah pekerja informal di mana umumnya bidang ini tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Ini bisa diartikan bahwa proses transformasi struktural belum menjamin kesejahteraan kelompok kelas menengah bawah," jelas riset BPS yang ditulis oleh Dhiar N. Larasati dan Ranu Yulianto, dikutip pada Kamis (21/12/2023).
Sementara kesenjangan pada akses perlindungan sosial juga terlihat jelas. Jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan memang sudah menjangkau lebih dari 60% rumah tangga di semua pendapatan.
"Namun, hanya 7,9% rumah tangga dengan pendapatan menengah bawah yang mendapatkan jaminan hari tua, jaminan pensiun, pesangon, jaminan kecelakaan dan asuransi kantor," tulis riset BPS.

Tak sampai setengah dari rumah tangga menengah bawah yang mendapatkan bantuan sosial. Akses kelas menengah bawah pada layanan kesehatan juga minim di mana dari 27% penduduk berpendapatan menengah bawah yang mengalami keluhan kesehatan, hampir 60% tidak melakukan rawat jalan.
"Kondisi ini memperlihatkan, kelas menengah tidak serta merta diterjemahkan sebagai penduduk berpenghasilan aman karena masih berisiko mengalami deprivasi," demikian dijelaskan oleh penulis.
Ekonom dan mantan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri dalam kolomnya di harian lokal menyebut, Indonesia perlu berkaca pada apa yang terjadi di Chile, negara di kawasan Amerika Latin.
Sejarah mencatat, demikian tulis Chatib, Chile menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Amerika Latin pada 2003 hingga 2019. Kemiskinan turun dari 53% menjadi 6% dalam tiga dekade. Namun, kinerja ekonomi itu tak cukup memberi jaminan kesejahteraan dan stabilitas.
Pada 2019 pecah demonstrasi besar-besaran di mana 1,2 juta orang turun ke jalan terpicu kenaikan tarif transportasi 4%, relatif kecil tapi berdampak luas. Situasi yang kemudian dikenal sebagai 'Chile's Paradox'.
Menurut Chatib, indikator ekonomi Chile memang membaik di mana ketimpangan juga turun. Akan tetapi, mengutip analisis Sebastian Edwards, Guru Besar Ekonomi Universitas California, Los Angeles, ada keterputusan makna ketimpangan per definisi para ekonom dengan pandangan rakyat Chile.
Sementara para ekonom hanya fokus pada ketimpangan pendapatan, rakyat Chile melihat fokus lebih luas termasuk kualitas hidup, interaksi sosial, akses terhadap kebutuhan pokok hingga keadilan dalam sistem ekonomi dan politik.
Berbagai kasus kolusi, kebijakan pemerintah yang berpihak pada kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan, kian mendorong kemarahan massa. "Kebijakan ekonomi dibuat untuk melayani yang berkuasa dan bukan untuk rakyat. Protes massa ditujukan pada privatisasi kebutuhan dasar, konsentrasi kekayaan, monopoli dan kolusi," tulis Chatib.
Keuangan Memburuk
Publikasi yang pernah dilansir oleh World Bank tahun lalu menyebut, kelas menengah Indonesia adalah orang dengan pendapatan antara Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan. Kelas masyarakat ini tumbuh 10% per tahun selama rentang waktu 2002-2016.
Pada 2020 lalu, jumlah penghuni kelas menengah mencapai 52 juta orang di mana sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Sementara kelas yang baru di tahap menuju kelas menengah (aspiring middle class) yakni mereka yang sudah lepas dari jerat kemiskinan tapi lebih rentan dibandingkan kelas menengah di atasnya, jumlahnya jauh lebih dominan mencapai 115 juta orang.
Mengacu pada hasil survei konsumen terakhir yang dilansir oleh Bank Indonesia pekan lalu, terlihat bahwa kelas masyarakat dengan tingkat pengeluaran menengah tengah menghadapi pemburukan kondisi keuangan, tidak berbeda dengan tekanan yang dihadapi oleh kelas bawah yang lebih rentan.
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini, yang mengukur persepsi masyarakat terhadap kondisi keuangan dan ekonomi sekarang dibandingkan enam bulan lalu, pada kelompok menengah yaitu mereka yang memiliki tingkat pengeluaran Rp3,1 juta-Rp4 juta perbulan, tercatat turun terdalam sebesar 4,8 basis poin menjadi 123,9 pada November. Sementara mereka yang memiliki pengeluaran antara Rp1 juta-Rp2 juta juga mencatat penurunan 2,6 bps.

Penurunan itu terjadi terutama karena penurunan Indeks Penghasilan Saat Ini sebesar 3,4 bps dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang bahkan amblas 8,5 bps. Sementara di kelompok dengan pengeluaran lebih rendah, penurunan indeks yang sama mencapai 7,5 bps dan 4,4 bps.
Di antara berbagai kelompok pengeluaran, kelompok Rp3,1 juta-Rp4 juta ini keluar sebagai kelas masyarakat yang paling pesimistis memandang prospek kondisi ekonomi ke depan dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen sebesar 2,7 bps. Sedangkan kelompok pengeluaran di bawahnya walau masih mencatat kenaikan IKK, tapi kisarannya masih di angka yang rendah di bawah 120.
Pengetatan moneter yang sudah dilangsungkan sejak Agustus tahun lalu, ditambah kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok mulai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), lonjakan harga beras, minyak goreng, telur, gula pasir hingga cabai-cabaian, menghantam kelompok masyarakat terutama kelas bawah dan menengah.
Fenomena makan tabungan alias mantab ditengarai sudah berlangsung untuk mengimbangi lonjakan harga kebutuhan hidup yang tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan karena sempitnya lapangan kerja.
Alokasi pendapatan masyarakat Indonesia yang digunakan untuk konsumsi secara umum turun 0,3% di kala pengeluaran untuk beban cicilan naik 0,5% dan alokasi untuk tabungan juga turun. Di mana kelompok dengan pengeluran Rp2,1 juta hingga Rp3 juta per bulan mencatat penurunan konsumsi terdalam hingga 1,4%.
Sementara bila mengacu pada data Lembaga Penjamin Simpanan, rekening dengan nominal saldo di bawah Rp100 juta mencatat tren penurunan dalam tiga bulan berturut-turut sejak Juli lalu.
Para analis BPS menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.
"Percepatan pembangunan infrastruktur pada aspek pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas dan aksesnya menjadi hal esensial di mana provinsi di wilayah tengah dan timur Indonesia seharusnya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur regional," jelas BPS.
Sementara Chatib menilai, berkaca pada kasus Chile, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kebijakan perlindungan sosial tidak bisa hanya difokuskan pada kelompok miskin. Pengalaman saat pandemi menunjukkan kelas menengah bawah juga terpukul tapi mereka tidak mendapatkan bantuan sosial.
Kedua, pembangunan ekonomi ke depan harus semakin inklusif.
"Dengan anggaran terbatas, mana yang lebih penting: infrastruktur atau perlindungan sosial? Indonesia butuh keduanya. Isunya bukan memilih di antar dua tapi bagaimana meningkatkan penerimaan pajak sehingga ekspansi sosial dan infrastruktur bisa dibiayai," jelas Chatib.
Ketiga, kelas menengah muncul membawa implikasi ekonomi politik di mana mereka hadir sebagai pengeluh profesional. "Kelas konsumen baru yang cerewet, kritis, dengan pendapatan yang lebih baik, akan menuntut kualitas pelayanan jasa publik, kualitas barang, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," kata Chatib.
Keempat, koefisien gini yang mengukur ketimpangan mungkin sudah lebih baik. Namun, kasus Chile menunjukkan Indonesia tidak bisa hanya fokus pada ketimpangan pendapatan tapi juga horizontal (social) inequality.
"Kita belajar dari pengalaman Chile: sikap pemerintah yang memihak pada oligarki, rasa keadilan yang terusik, dan politik transaksional di kalangan elite, akhirnya mendorong gejolak sosial," jelas Chatib.
(rui/aji)