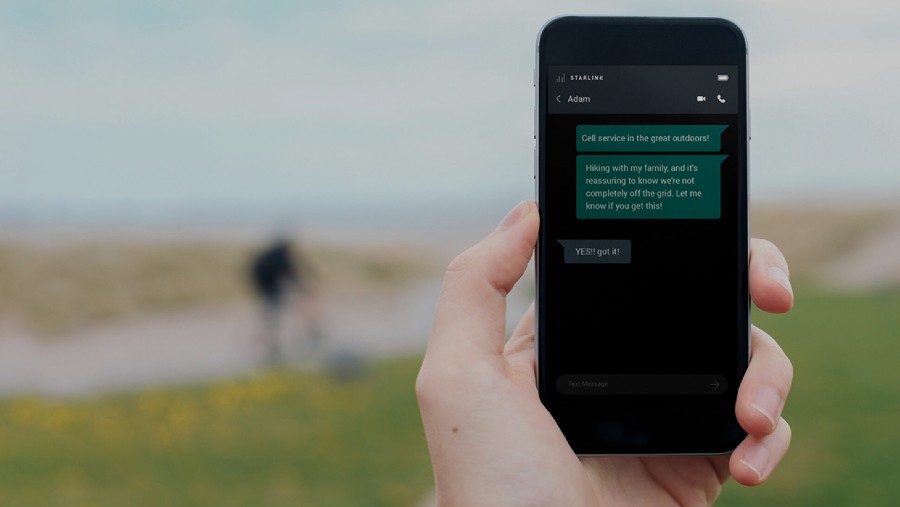Namun, Marwan menyatakan bahwa biaya satelit Starlink terbilang mahal. Harga perangkat yang menerima sinyal Starlink, yang merupakan jenis router, di Malaysia dapat mencapai hingga Rp8 juta.
“Starlink di Malaysia ini sudah launching. Expensive. Harganya kira-kira Rp8 juta,” bebernya.
Selain itu, bisnis penyelenggara telekomunikasi nasional seperti operator seluler, jaringan tertutup (Jartup), dan penyelenggara Satelit Geostasioner (GSO) bisa terancam dengan kehadiran Starlink.
Karena itu, Marwan menegaskan bahwa agar Starlink tidak mengganggu bisnis yang sudah ada di Tanah Air, satelit Starlink harus diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Untuk yang kontra, jika tidak diatur secara tepat, bisnis Starlink berpotensi bisa mengancam bisnis penyelenggara telko [industri telekomuniasi] nasional seperti seluler, Jartup, dan penyelenggara satelit GSO,” ungkap dia.
Dia juga menegaskan bahwa Starlink belum memiliki izin penyelenggara jasa sebagai Internet Service Provider (ISP) di Indonesia.
“Starlink pun masih memakai IP (internet protocol) global, sehingga berpotensi ada isu PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan kedaulatan negara,” ujar Marwan.
Dimulai dengan itu, ATSI menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan baru jika Starlink benar-benar hadir di Indonesia.
Pertama, Starlink harus berfungsi sebagai layanan bisnis ke bisnis (B2B), bukan bisnis ke konsumen (B2C).
Kedua, Starlink harus bekerja sama dengan penyedia satelit di Indonesia.
Ketiga, satelit Starlink harus memiliki hak labuh atau landing rights.
Keempat, alokasi penomoran IP Indonesia harus digunakan oleh satelit Starlink.
Kelima, mereka perlu membangun server dan fasilitas pemulihan bencana (DRC) di Indonesia.
"Terakhir, mereka harus comply [patuh] terhadap regulasi Lawful Interception [penyadapan legal] di Indonesia, dan sebagai penyelenggara jasa, Starlink harus dikenakan kewajiban untuk membayar BHP [Biaya Hak Penggunaan] telekomunikasi dan USO [Universal Service Obligation],” tukasnya.
(ros/wep)