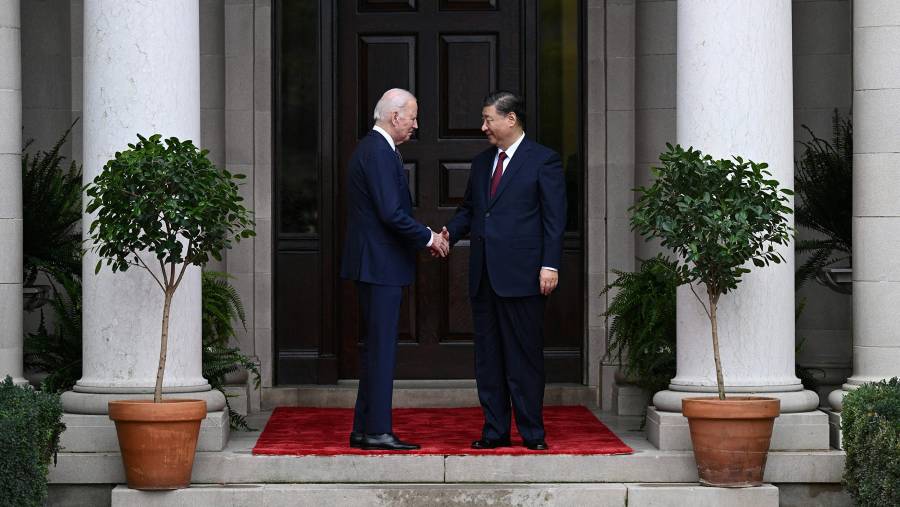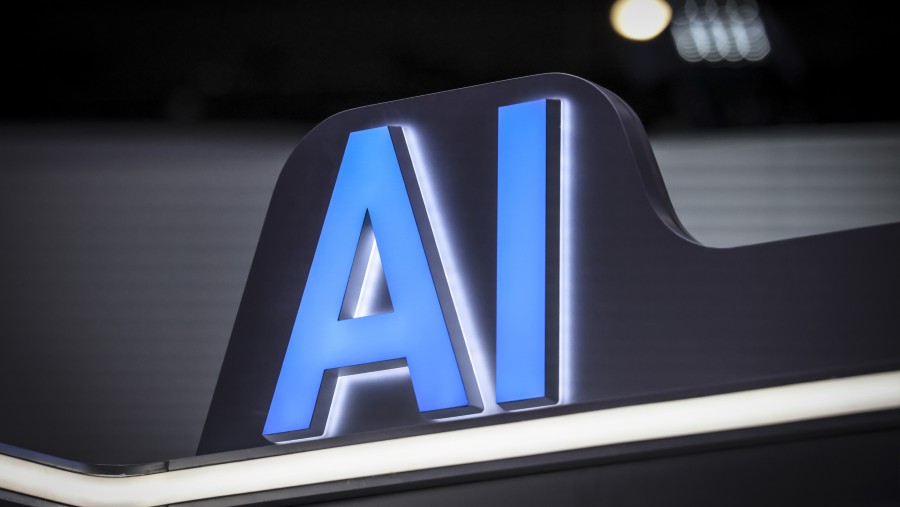“Itu yang menjadi tantangan. Selain itu, teknologinya belum tentu efisien untuk menggantikan impor LPG [liquefied petroleum gas/gas minyak cair] untuk listrik,” lanjut Bhima.

Problem Paling Inti
Salah satu problem paling inti dari proyek gasifikasi batu bara adalah pendanaan. Terlebih, perusahaan yang mau berinvestasi di sektor batu bara saat ini makin sedikit lantaran mereka sangat memperhatikan rekam jejak komitmen lingkungan dalam portofolio pendanaannya.
“Mereka terikat dengan standar ESG [environmental, social, and governance]. Artinya, kalau ESG-nya turun, proyek gasifikasi ini pembiayaan atau bunganya akan sangat mahal. Jadi ini yang menjadikan proyek ini terkesan dipaksakan, padahal belum tentu menarik secara finansial dan hitung-hitungan bisnis.”
Menurut Bhima, dengan dalih penghiliran industri sekalipun, megaproyek gasifkasi batu bara masih terkesan dipaksakan.
“Batu bara itu sudah stranded [kandas] dan nanti akan kontradiksi. Kita sudah mau pensiun dini PLTU dengan tujuan mengurangi ketergantungan batu bara, tetapi kalau ada proyek gasifikasi kan jadi kontradiktif dengan komitmen lingkungan kita, meski bentuknya gasifikasi,” tegasnya.

Insentif Saja Tak Cukup
Dari kaca mata pengusaha, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menilai insentif tambahan, yang akan diberikan pemerintah untuk proyek penghiliran batu bara, tidak akan cukup ampuh mendongkrak investasi di bidang gasifikasi komoditas energi fosil tersebut di dalam negeri.
Dia tidak menampik beberapa insentif yang diberikan kepada perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebenarnya sudah cukup menarik dan sesuai dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Misalnya, kata dia, dalam hal pembebasan iuran produksi atau royalti kepada perusahaan yang sudah menjalankan penghiliran batu bara serta insentif masa berlaku IUP. Walakin, dia tidak mengelak masih banyak isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.
"[Insentif-insentif] Itu positif jadi ada jaminan ke arah sana. Namun, balik lagi, untuk jadi bisa tangible [konkret manfaatnya], apakah cukup insentif-insentif tadi? Belum tentu," ujar Hendra.
Dia juga mengakui salah satu isu dalam penghiliran batu bara adalah kebutuhan biaya yang tidak sedikit untuk memulai proyek gasifikasi komoditas tulang punggung ekspor nonmigas tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah mulai mewajibkan korporasi-korporasi batu bara —termasuk Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro, Arutmin, Kideco— untuk melakukan penghiliran sebagai syarat memperoleh perpanjangan IUP. Permasalahannya, pengusaha ditantang oleh kesulitan mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan, padahal proyek gasifikasi membutuhkan investasi dalam jumlah besar.
Untuk itu, dia menilai insentif pembiayaan dinilainya bakal lebih efektif mengatrol investasi proyek gasifikasi batu bara di dalam negeri.
"Ya selayaknya investasi, ya harus ada financing [pendanaannya], gitu. Nah, itu yang jadi masalah karena kan untuk proyek baru, pendanaan kan susah apalagi untukk proyek yang coal-related," terangnya.
Isu lainnya adalah belum cukupnya sektor industri hilir lain di dalam negeri yang dapat menjamin serapan produk derivatif gasifikasi batu bara, seperti dimethyl ether (DME), metanol, gas sintetik, maupun hidrogen dan amonia.
"Jadi jangan semua dibebankan ke industri pertambangan batu bara kan? Balik lagi ke basic yang saya sebutin tadi, kita kan tambangnya batu bara, kita tahu bara, tetapi kita enggak tahu pasarnya LPG dan gas sintetik [yang merupakan produk turunan gasifikasi batu bara] ini," jelasnya.
Selain itu, harga jual produk turunan batu bara dinilai belum kompetitif melawan harga gas dan LPG. Dengan demikian, pengusaha juga membutuhkan jaminan aturan harga yang konsisten dari pemerintah, mengingat gasifikasi merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan kepastian serapan pasar.

Untuk diketahui, proyek penghiliran batu bara di Indonesia —khususnya untuk diolah menjadi DME sebagai substitusi LPG— masih terkatung-katung hingga saat ini, setelah ditinggal hengkang oleh investor Amerika Serikat (AS) Products & Chemical Inc (APCI).
APCI awal tahun ini mundur dari megaproyek gasifikasi batu bara, yang dipenggawai oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA), untuk fokus pada proyek hidrogen biru di negara asalnya dengan janji insentif yang lebih menggiurkan dari pemerintah Negeri Paman Sam.
Menteri ESDM Arifin Tasrif belum lama ini mengatakan pemerintah masih terus berburu calon pengganti APCI untuk disandingkan dengan PTBA dalam menggarap proyek DME itu. Hingga kini, sayangnya, belum ada investor kakap yang bersedia masuk ke proyek itu.
Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan pun menyinggung bahwa proyek gasifikasi batu bara dapat mengurangi beban subsidi energi untuk LPG senilai Rp7 triliun per tahun.
Proyek mercusuar oleh PTBA dan APCI sejatinya direncanakan selama 20 tahun di wilayah Bukit Asam Coal Based Industrial Estate (BACBIE) yang berada di mulut tambang batu bara Tanjung Enim, Sumatra Selatan. BACBIE akan berada di lokasi yang sama dengan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8.
Dengan mendatangkan investasi asing dari APCI senilai US$2,1 miliar atau setara Rp30 triliun, proyek itu awalnya digadang-gadang sanggup memenuhi kebutuhan 500.000 ton urea per tahun, 400.000 ton DME per tahun, dan 450.000 ton polipropilen per tahun.
Menyitir pernyataan resmi Pertamina, dengan utilisasi 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini diklaim dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahun untuk mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun sehingga dapat memperbaiki neraca perdagangan.
(wdh)